TERHIMPIT GELOMBANG
 Pagi itu, dalam kalut
dan kabut. Remaja itu akan kembali menginjak tanah halaman. Di sana lah ia
terlahirkan, tempat mengeja kata demi kata. Juga, tempat ia mengenal cinta. Ya,
sebentang tanah titipan Tuhan, karena ia yakin semuanya bakal kembali kepada
Tuhan. Kampung itu terhampar di ujung Pesisir Selatan, tepatnya di garis perbatasan
dua propinsi. Perkampungan yang masih hijau dengan budaya dan pepohonan. Anak
sungainya pun masih mengalir dalam peredaran.
Pagi itu, dalam kalut
dan kabut. Remaja itu akan kembali menginjak tanah halaman. Di sana lah ia
terlahirkan, tempat mengeja kata demi kata. Juga, tempat ia mengenal cinta. Ya,
sebentang tanah titipan Tuhan, karena ia yakin semuanya bakal kembali kepada
Tuhan. Kampung itu terhampar di ujung Pesisir Selatan, tepatnya di garis perbatasan
dua propinsi. Perkampungan yang masih hijau dengan budaya dan pepohonan. Anak
sungainya pun masih mengalir dalam peredaran.
Ia masih ingat, dulu
tanah titipan Tuhan ini juga kawasan kerajaan Ranah Minang. Bahkan sampai sekarang,
tepat di taman kota daerahnya masih berdiri kokoh Rumah Gadang, rumah adat Minangkabau. Hanya saja ia tidak begitu
ingat kapan tanah kelahirannya terpecah dari Sumatera Barat. Sudahlah. Baginya,
dimana pun ia melangkah, ia tetap bangga tanah kelahirannya, bangga dengan
Indonesia. Ia bangga pada negeri ini. Dan kini, ini kali pertama ia tinggal di Minang,
menginjak tahun pertama menyandang gelar mahasiswa.
“Dek, Maaf. Ado ndak yang
duduk di sini?” Seorang perempuan paruh baya menyapa dengan senyum mengambang.
Bahasanya campuran; Indonesia-Minang.
“Eh...ti.. ti..tidak,
silahkan” ia menjawab kikuk. Kembali ia melemparkan muka ke jendela. Ia
terlihat tenang melihat lautan lepas di Teluk Bayur. Sungguh indah. Perahu
kecil melintasi deretan kapal-kapal pengangkut barang. Ia diam dalam-dalam,
menikmati pesona keindahan alam ciptaan-Nya. Lambat-lambat, wajah kapal kian
menghilang dari pandangan. Lautan pun semakin menjauh dari sorotan mata, kini
hanya tampak rerimbunan pohon yang menghijau. Jauh, semakin jauh dan
menghilang.
Sesekali matanya ia lemparkan
ke depan. Kadang mata terpejam. Dan sekali-kali pula ekor matanya melirik ke samping
kiri. Wanita paruh baya itu terlihat beberapa kali menguap, dan mulai terkantuk-kantuk.
Bus semakin melaju meninggalkan Ranah Minang. Kini semakin jauh. Suasana mulai
terasa sepi. Hanya deru angin berbisik berisik. Kiri-kanan tertidur pulas, begitu
pula dengan wanita paruh baya itu. Hanya satu-dua orang saja yang bertahan. Bahas
ini dan itu. Entah apa topiknya. Ia tak perduli, bagai bungkam alam sepi. Ia
mengeluh.
.......................
Oh...mato
balinangan takana kampung, tabayang sayang
Iyo
indak tatahan, taragak kama dikadukan.
Oh...tinggalah
dulu kampuang halaman, tinggalah tapian
Iyo
antah pabilo nan den sayang yo dapek den jalan
...................
Lagu minang terdengar.
Ya, persis yang ia rasakan. Rindu. Kangen yang semakin dalam pada kampung halaman. Meninggalkan orang tua. Terlebih
lagi pada kekasih yang ia cintai dua tahun lalu. Adik kelas SMA-nya.
“Ah, tahu betul Bang
Sopir ini lagu kesukaanku”, gumamnya dalam hati. “Mungkin juga dia merasakan
hal yang sama. Aku yakin dia juga hidup di perantauan. Faktanya, nggak ada. Tapi
ini Bus Antar Propinsi, yang sering keluar kota meninggalkan ranjang. Boleh
jadi ia sedang rindu kampung halaman. Terdera sibuk keluar daerah mencari
nafkah. Atau mungkin, hanya iseng-iseng saja memainkan lagu sendu, penghilang
kantuk.” Ia terus meracau dengan pikirannya sendiri. Mencari teka-teki.
“Ah, sudahlah”, Ia
berusaha menghilangkan tentang itu. Dan, terus memori otaknya mengingat kata-kata
sibuk yang sering menghantuinya selama ini. Sibuk. Benar, akhir-akhir ini ia sering
menerima balasan SMS di Handpone buntutnya;
Maaf, sedang sibuk. Ia bahkan, juga telah
bosan mendengar nasihat operator Handpone
ketika melakukan panggilan; Maaf,
nomor yang anda tuju sedang sibuk, cobalah beberapa saat lagi. “Sesibuk
itukah Dia?”, ia mengeluh. Sibuk! Begitu gampangnya. Ya, atau mungkin hanya
alasan. Entahlah. Ia terdiam.
***
“Ayo, yang mau makan
silahkan turun!”, Sopir itu bersuara keras bagai speaker di mengetuk gendang telinga.
Ia terjaga dan terlihat kusut. Perjalanan itu membuat ia tertidur sekitar dua jam.
Ia tahu setelah melihat handpone-nya. Di luar sana, terlihat sebuah Ampera. Kiri-kanan,
rumah masih terlihat jarang, tak sepadat kota Padang, atau kota metropolitan. Di
belakang, suara ombak menghempas, mengejar pasir putih dengan girang.
“Mbak, Mbak, gak makan?
Maaf, numpang lewat Mbak?” Wanita itu memberi sedikit rongga. Ia berlalu
meninggalkan wanita paruh baya yang sedari tadi tidur di samping tempat
duduknya. Ia cuek, tidak perduli. Lalu menuju kamar mandi untuk mencuci muka
kusamnya. Berulang kali wajahnya disiram. Sejuk, ketika air mengaliri pori-pori
kulit sawo matangnya. Wajahnya kembali segar. Lama-lama ia pandang pada kaca
yang terpajang di dinding papan. Ya, kaca itu nampaknya sudah lama retak. Ia
takut, kalau retak itu juga berlaku pada dirinya. Lihatlah, kini ia juga takut hatinya
dipetak-petak seperti kotak. Tidak mungkin.....
“Sudah
belum?” suara dari luar. Gontai ia buka pintu kamar mandi itu. Melangkah menuju
bus yang terparkir di halaman Ampera.
“Eh...Buyung.
Nggak makan?” tanya Sopir. Ia menggeleng pelan. “Tadi saya sudah makan roti”, sahutnya.
“Yakin,
perjalanan kita masih jauh,” kata Sopir.
“Insyaallah Bang”, sahutnya. Kini
giliran Sopir menggeleng-geleng. Sambil mengempal suapan bertubi-tubi. Di atas
Bus itu, ia menghempaskan pantatnya di tempat semula, tepat di bangku deretan
ketika dari depan. Sambil meneguk air mineral, matanya mengamati suasana daerah
di Ampera itu, masih tampak asri.
“Buyung, serius kenyang
makan roti?” Sopir itu menyapa dengan pukulan ringan di bahu. Ia terkejut, dan memberi
jawaban anggukan.
“Maaf. Bye
the way, karena uang habis?” Sopir itu memukulnya dengan pertanyaan, dan mulai
menstarter mobil, dan melaju perlahan-lahan. Ia mulai menunduk, tanpa jawaban. Pertanyaan
sederhana, dan sok ke-Inggris-an itu bagai peluru menembus telak jantungnya. Dadanya
nyesak, berdegup kencang. Ada sesuatu yang mengirisnya. Pedih. Tanpa dipaksa matanya
memerah, tapi ia berusaha tegar. Sopir itu benar, ia memang tidak mempunyai
sisa uang untuk makan. Adanya, hanya bisa membeli cemilan roti ringan dan
sebotol air mineral. Ia masih bersyukur, karena masih ada yang bisa disalurkan
dalam lambungnya yang kering. Maklum saja, ia anak kuliahan. Orang tuanya,
tidak lebih dari petani biasa. Lama ia tertegun ditembak pertanyaan itu.
“Yung, sekali lagi maaf.”
Kata Sopir. Ia menatap ke jendela kaca, “Ya, nggak apa-apa Bang”, sambutnya
lirih. Bagai air di atas sehelai daun, kemudian pelan-pelan jatuh berderai. Sekali
lagi tanpa dipaksa. Menjalar mengikuti pori-pori, semakin membasah. Buru-buru
ia menghentikannya, menyeka dengan tangan. Tentang air mata itu, sama sekali bukan
karena pertanyaan Sopir, tapi rasa bersalahnya yang mendera. “Aku memang anak durhaka,
yang tidak pernah berterima kasih pada orang tua. Selama ini, yang mereka
lakukan demi aku. Tapi kini, aku telah menyia-nyiakannya. Aku lebih memilih
cinta. Bodoh! Kenapa tidak memilih Surga di bawah telapak kaki Emak.” Ia
memaki-maki dirinya sendiri dalam hati. Dadanya sesak. Perih.
***
Lama suasana hening.
Hanya lagu-lagu galau 90-an masih berdendang kencang. Ia, yang di pojok sana masih
terdiam bisu. Ia teringat masa lalu. Derita anak petani, yang pernah putus
sekolah setelah Madrasah Tsanawiyah. Kini, ia mahasiswa yang baru menginjak
tanah kota, demi menjemput asa. Dan, terlalu telah jatuh hati pada setangkai
bunga bermahkota. Bus tetap melaju. Ia masih tetap diam, bermain dengan hatinya
sendiri. Keluarga di kampung, orang tua, kakak, dan juga adiknya. Perasaan bersalah
itu yang selalu datang menghantuinya.
Ia masih ingat betul,
pesan Emaknya enam bulan yang lalu. Ketika ia pulang dengan buah tangan. Ia
melangkah pelan, melihat rumah dari kejauhan. Ia dapati senyum sumringah
keluarga di halaman. Sungguh, adik-adiknya begitu senang. Semuanya happy. Kini, ia tidak membawa apa-apa, sekedar
tangan hampa. Memang, ia di Padang bukan mencari uang, tapi ilmu. Tentu,
setidaknya oleh-oleh ilmulah yang bakal ia berikan. Bukan luka. Mereka tidak
butuh itu.
Ia tahu. “Sudahlah, Sabar.
Adikmu pasti mengerti, mereka bukan mengharapkan oleh buah tangan, tapi kehadiranmu.
Mereka rindu.” Kata Mak-nya di telepon seminggu yang lalu. Pandai betul Mak-nya
menghibur. Tapi, tetap saja ia sedih. Ia tidak sampai hati, namun sudah
terjadi. Selama puluhan tahun, Mak-nya hafal benar menu kesukaannya; tumis
bayam, atau sambal berulam pucuk ubi. Sedang soal cinta, ia tidak pernah cerita
sama sekali. Ia takut.
Tapi waktu itu; enam bulan
yang lalu. Selepas magrib. Sesudah makan bersama dalam satu meja. Seusai
bersenda gurau dengan keluarga. Ia ingin meminjam motor, mohon izin untuk
keluar mencari angin. Ia dipatahkan dengan kata-kata. Bahasa lembut Mak-nya; “Mak
tahu. Kami semua di rumah ini tahu. Kamu sangat mencintainya kan? Adik kelasmu ketika SMA dulu. Menurut Mak,
ada baiknya tidak usah. Mak takut kamu menangisi cinta. Cinta itu bagai api
dalam sekam; baranya membakar, asapnya menciptakan air mata. Di kampung ini,
siapa yang tidak tahu? Dia hanya cocok dengan tetangga sebelah. Kita miskin. Jauh
panggang dari api untukmu, Nak!” Mak-nya berjelas-jelas penuh hati-hati.
Ia terkejut, bagai diledak
sebongkah granat teroris di pengasingan. Dari mana Mak-nya bisa tahu. Ia tidak
pernah sama sekali bercerita, keluh-kesah kisah cinta. Kemudia ia tertunduk
malu, kecewa, sedih, bersatu-padu menyerang jiwanya. Terlebih lagi, pernyataan larangan
itu. Tentang ketidakcocokkan itu. Memang, Mak-nya benar. Sedikit ada rasa
sesal. Sungguh malang, ia tidak ditakdirkan dalam keluarga berada. Nafasnya
tertarik dalam-dalam, dan ia lepas dengan
rasa syukur. Hatinya masih bertanya. Apakah cinta hanya memandang satu
sudut? Entahlah! Ia terdiam, hening.
“Saya ini Mak-mu. Naluri
ibu pada seorang anak, bagai daun diujung ranting. Kuat. Ia tidak akan terlepas
begitu saja, meski dihempas badai. Denyut jantungmu, jantungnya Mak. Nadimu, juga
nadi Mak. Nak, kamu tahu? Dia mengaku nggak pernah jadi pacarmu. Dan, tidak lebih
dari sebatas teman. Sudahlah. Cinta itu jangan dikejar, karena ia akan terbang
setinggi mungkin. Bersabarlah Nak, seperti namamu, esok ia akan datang. Mak
yakin, pasti ada yang lebih baik. Itu janji Tuhan kita.
Ingat, kita ini bukan
orang miskin. Tapi takdir yang memutarbalikkan nasib. Memang kita bukan seperti
keluarga sebelah, tetangga kita. Itu juga atas takdir. Bangunlah Nak, jangan
mimpi terlalu tinggi soal cinta. Namun mimpilah cita-cita setinggi mungkin. Yakinlah,
suatu saat cinta pasti mendekat. Sekarang lebih baik kamu istirahat. Besok,
biar bisa membantu Abah-mu ke kebun untuk biaya kuliahmu.” Penuh hati-hati
Mak-nya memberi nasihat.
Kini, dalam perjalanan
hijrah ke kampung, ia bingung. Bekas-bekas nasihat itu masih tertanam dalam
ingatannya. Jejak-jejak cinta dan rindu masih membayang dalam hati pencari
cinta. Dadanya terasa sesak, bagai ruangan tanpa udara. Telinganya ngilu mendengar
kata-kata Mak-nya, tentang penghianatan Dia yang di sana. Ia merasa aneh, kemana
hadiah-hadiah itu. Kemana pula buku, boneka, jilbab putih, hitam, dan berwarna
ungu itu. Bukankah semua itu untuk hadiah ulang tahun dan Happy New Year tahun lalu? Ah! ia kesal.
Matanya menengadah di
awang-awang. Melihat sarang laba-laba di pasak rumah. “Kenapa begitu bodoh!
Kenapa aku terlalu percaya kepada tetanggaku. Ternyata bukan dongeng, dan ini
jelas bukan dongeng. Tukang pos juga manusia, yang bisa merebut cinta.” Dalam hati, ia menyesali sikapnya sendiri. Tetap,
di mata Mak-nya, ia berusaha tegar, tak tampak kesedihan. Ia tidak ingin
terlihat lemah, ia takut menyakiti hati Mak-nya.
Roda bus masih berputar,
mengitari lika-liku tikungan tajam. Naik-turun. Perjalanan masih panjang. Butuh
dua jam lagi untuk sampai tujuan. Kemudian bus mendadak berhenti. “Semangat! Tetaplah
tersenyum dalam meraih cita-cita dan cinta.” Suara wanita paruh baya yang sejak
tadi di sampingnya berlalu. Menuruni pintu bus. Ia telah sampai, di Tapan Basa
Ampek Balai.
Ia heran. Siapa wanita
itu, kenapa ia tahu? Ia merasa ada keganjilan. Ia pejamkan mata erat-erat, menghilangkan
ke anehan itu. Ketika matanya terbuka tabir surya telah ditutup senja. Bibir pantai
mencumbu dengan langit warna jingga. Matahari hilang ke peraduan, dan diganti
dengan bulan dan bintang. Perjalanan itu masih panjang. Bersabar menjemput asa.
Dalam bimbang, ia terlelap bersama malam. Bunga rampai bertabur di atas
pekuburan.
Padang,
24 September 2013
(Pernah dimuat di Koran Singgalang-Minggu 2013)
Penulis: Wahyu Amuk
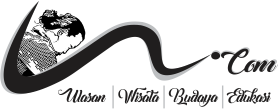





0 Comments
Jika bermanfaat tolong sebarkan dengan mencantumkan sumber yang jelas. Terima Kasih !