“Sruuuupp....” aku menghirup dalam-dalam pada pinggir mug berwarna putih dengan motif bunga. Lalu mengernyit kening, sambil menatap dalam-dalam langi-langit beranda di lantai dua. Sebuah rumah berwarna biru, tempatku menghabiskan separuh waktu di tanah rantau, kota Bingkuang kotanya orang Padang.
Dua gelas sudah kopi
kuhabiskan. Demikian pula malam kian larut, pekat, dan
menghitam. Aku semakin hanyut dalam kelam dan kenangan masa
silam. Otakku masih terkenang masa lalu, ketika pertamakali kau seduhkan segelas
kopi untukku. Waktu itu, tepat di atas atap rumahmu langit sedang ditaburi bintang dan cahaya
rembulan. Kau tersenyum malu-malu, membuatku semakin lugu
dan terlihat
bodoh saja waktu itu.
“Minumlah. Cobalah dulu disentuh kopi buatanku. Jika terlalu pahit, nanti
aku tambahkan gula,” bibirmu bergetar sedikit parau kala itu memecahkan suasana, disela iringan suara jangkrik yang berdendang di sudut pagar halamanmu.
Aku hanya menggangguk pelan. Kemudian meraih gelas Coffe Cup bertuliskan zodiak Sagitarius. Dan meneguknya seteguk dua
teguk. Di depanku kau terlihat semakin cemas dan kaku.
“Tidak apa-apa, kopinya enak
kok,” ucapku menimpali raut mukamu waktu itu.
“Terlalu pahit ya? Maaf!” Ucapmu serius.
“Enak kok.” Kataku mantap.
Kau tahu sayang, aku bukanlah lelaki pecandu kopi, dan aku tidak pula pernah mengerti kriteria kopi yang enak. Tapi waktu itu, aku tetap
ikhlas mengatakan kopi buatanmu enak. Dan bahkan, berapa kalipun kau bertanya,
aku akan memberi
jawaban yang sama. Enak! Meskipun di kerongkonganku pahitnya tertanam. Sungguh, aku tidak ingin membuatmu kecewa. Aku tidak mau kopi sajianmu
sia-sia. Bagiku, bersamamu biarlah aku menjadi candu.
Sejak meneguk kopimu malam itu, mataku tetap jalang dan tak mau terpejam
sampai matahari datang hingga petang kembali tenggelam.
Sungguh berat racun kopi yang kau buat untukku sayang. Bubuk sianida yang kau
taburkan hampir sekarat aku dibuatnya. Namun sejak saat itu pula, aku selalu menjelangmu dengan berbagai alasan.
Modusku agar bisa meneguk kopi pahitmu. Aku telah menjadi candu padamu.
Kau tahu, semenjak aku
mengenal malam, gulita adalah keajaiban. Bagiku, siapa lagi yang menciptakan
malam sepekat ini, selain Tuhan. Dan semenjak meneguk kopi pahitmu itu aku semakin tahu, memandangmu ialah suatu keajaiban dari Tuhan. Dengan secangkir kopi hitammu yang memikat. Sianida cintamu, membuat hatiku terikat.
***
Sampai kini, aku masih ingat
satu hal tentang kepekatan itu. Tentang pekatnya segelas kopi yang pernah kau
letakkan di atas lantai depan rumahmu. Ingatkah kau, disitu dulu kita
berselonjor kaki sambil merangkai sajak cinta. Sekali-kali menghirup kopi
pahitmu, yang hitam, kental, dan menggigit. Sambil menatap rembulan, kau bilang
kopi itu sengaja kau racik dengan anggun oleh jemari lentikmu. Ditabur sedikit
rindu, dan tanpa gula. Ya, itu kopi terakhir darimu. Sebelum kau pulang,
membenam segala rasa di kampung halamanmu.
Sekali lagi aku katakan, dulu
aku bukan pecandu kopi. Aku penikmat teh dan susu. Jika tidak ada teh dan susu,
aku hanya meneguk air putih. Orang bilang, dan dari beberapa artikel yang
pernah aku baca hasil searching di google, katanya air putih lebih sehat. Sebab
itu pula, aku lebih memilih air putih dibanding kopi. Aku takut seperti Abah di
kampung. Umurnya belum begitu tua, meskipun tak lagi muda. Tiap malam ia
meraung-raung, mengaduh menahan sakit, dan tubuhnya semakin ringkih. Tak jarang,
ketika aku pulang kampung seringkali memijat badannya, terutama bagian betisnya.
Sambil meraung-raung pula ia menahan sakitnya. Aku tak tega. Sungguh!
Dokter bilang, itu akibat
candu kopi. Jika tidak menghirup seseduh kopi saja, akan membawa rasa sakit
pada bagian tubuh. Syukurnya, lambat-laun Abah tidak lagi menikmati kopi. Sudah
diganti dengan teh dan susu. Ia pernah bilang, minuman teh dan susu tidak
berasa. Demi kesehatan, ia hilangkan rasa candu yang dulu.
Abah pernah bilang; “Buyung,
jangan kau tiru perangai Abah. Jaga kesehatan kau sebelum datang sakit.
Manfaatkan waktu muda sebelum tua seperti Abah,” tanpa melirikku disela
batuknya.
Kini apa dayaku. Candu
kopimu memperdayakanku. Lupa aku tentang nasihat Abahku itu. Setiap detak jam
berdetik, ingin rasanya semakin sering aku bertandang ke rumahmu. Sekedar
menyapamu, melihat sekilas senyum, dan menunggu segelas kopi darimu. Sebab,
sudah terlanjur. Canduku pada kopimu, ibarat selera semut pada gula. Semesta
pun tahu, sukaku pada kopimu, diumpamakan rindu sepucuk daun pada hujan,
menunggu ia jatuh meskipun penantian demikian panjang.
Kau bisa ingat, atau sudah
lupa hari itu. Sabtu malam, di penghujung tahun yang lalu. Langit berwarna
hitam, gendang gemuruh mulai bertalu-talu, dan kilat berkembang api. Pertanda
hujan lebat akan turun, menyirami bunga-bunga di halamanmu. Aku tak surut
sedikitpun menghirup kopi pekat buatanmu. Tapi bibirmu, tiba-tiba seayun dengan
suara langit yang akan menjatuhkan hujan.
“Besok aku akan pulang.
Tunggu aku kembali membawa kopi spesial untukmu. Kopi Bubuk cap Kapal Tanker
dari Batam-Tanjung Pinang,” katamu menatapku dengan janji harapan.
Tiba-tiba langitpun urung
menghujamkan bumi, dan langit pelan-pelan cerah seketika. Entah pertanda apa.
Aku bingung. Bintang di langit pun sedemikian terang.
***
Oh Ulfah, setangkai bunga dari kepulauan. Membawa temu di tanah rantauan. Sayang! Lama sudah kopimu menghilang, sejak waktu semakin bergulir hingga berganti musim. Kini kabarmu tak pernah lagi berkirim angin. Aku di ranah Minang memegang erat siluet wajahmu di Pantai Padang. Menanti aroma kopimu yang hitam. Sayang!
Oh Ulfah, setangkai bunga dari kepulauan. Membawa temu di tanah rantauan. Sayang! Lama sudah kopimu menghilang, sejak waktu semakin bergulir hingga berganti musim. Kini kabarmu tak pernah lagi berkirim angin. Aku di ranah Minang memegang erat siluet wajahmu di Pantai Padang. Menanti aroma kopimu yang hitam. Sayang!
Gila aku pada kopimu. Bahkan,
ketika melihat iklan kopi di Televisi saja, aku sudah terkenang kopimu. Melihat
gelas ketika minum pun, aku kembali mengingat zodiakmu. Bahkan, ketika hujan
datang aku merasakan karakter kopimu. Pekat hitam langit malam, mengingat aku
tentang warna kopimu. Begitu aku mengenang kopimu, merindu raut wajahmu.
Sayang!
Begitu gilanya aku pada kopimu.
Bahkan waktu sebelum kau pulang, aku pernah bertanya, perihal racikan kopi
buatanmu. Aku terima jawabanmu, “hanya dengan hati”. Sesederhana itu jawabanmu.
Padahal, waktu itu aku berharap menerima jawaban satu sajak darimu. Sayang!
Ulfah, kuharap kamu masih
ingat, tentang kenangan yang pernah kita taburkan pada segelas kopi. Meneguk,
seteguk-dua teguk kopi yang kau buatkan. Menghisap dan menghirup pekat segelas
kopi berdua. Kau masih ingatkah? Kita di satu-dua jam, atau bahkan beberapa jam
pada bulan sebelum kau pulang, satu meja, satu laptop, buku dan pena. Kita
memegang segelas kopi bersama, sambil merangkai dan mengeja tentang cinta, pantai,
hujan, bunga, dan rembulan. Waktu itu kulihat alangkah bahagianya kau,
begitupun juga aku.
“Biarkan semesta tahu.
Biarlah kita tetap selalu bersama, sampai kita tenggelam bersama pekatnya kopi
ini,” bisikmu di daun telinga. Dan kau peluk aku dengan manja.
“Semoga hujan tetap dalam
takdirnya. Semoga kita di dalam takdir doa kita pula” aku membalas doamu.
Pada doa-doa itu aku percaya
pada janji Tuhan semesta alam. Aku pun percaya, karena kita penggemar sastra,
dan mengoleksi karya-karya ternama. Hanya saja, aku juga suka bicara tentang
dunia politik, terutama kebijakan pemerintah dan polemik para pemimpin saat
ini. Sebaliknya, kau tidak. Kau hanya asyik dan tidak bisa berali dengan dunia
sastra dan filsafat.
Sayang! Aku hanya ingin
bertanya. “Ada apa?” Entahlah, sebabnya beberapa bulan terakhir ini kau mulai suka
dengan dunia politik. Kau bahkan membeli buku-buku politik. Aku tdak tahu
maksudnya. Kau tidak pindah haluan bukan? Sejak kau suka politik itu pula, aku
tidak pernah lagi mencicipi dan bahkan menghirup aroma kopimu. Kau hanya asyik bersenda-gurau
dengan politikmu. Kau pun mulai candu pada dunia pemerintahan, dan pejabat yang
dulu kau benci itu.
Sayang! Dunia kini memang
aneh dan rada edan. Kenapa kau ikut-ikutan pula. Duniamu tidak bisa lagi
kutebak kemana arah dan tujuannya. Kau perempuanku yang hilang. Sesuatu yang semula
kau benci, kini kau pertuhankan. Dan kini aku, yang kau titipkan harapan dulu seakan-akan
amnesia di dunia nyata. Kau begitu benci sayang. Kau semakin hilang akal. Kau
begitu muak ketika gelas kopimu kugenggam kembali. Bukankah kau yang
pertamakali menyuguhkannya?
Ulfah, sayang! Aku
sedemikian candu pada kopimu. Terkapar oleh sianida rasa rindu, memabukkan
sayang. Nyatanya, kau berlalu begitu saja. Kini dengan lantangnya kau berkoar,“
politik itu perlu, agama saja mengajarkan kita berpolitik,” tantangmu dengan lantang.
Padahal setahuku, kau sangat
anti dengan dunia perpolitikan. Dulu, segala yang berbau pejabat kau laknat.
“Pejabat sekarang tidak becus, tetapi rakus, seperti tikus-tikus got yang yang
selalu merongrong di kolong. Setelah mendapat jatah, uang rakyat dimakan dengan
sumpah-serapah,” koarmu. Spontan aku ikut mengangguk, setuju. Sebab, aku sangat
suka membahas dunia politik yang semakin berbau pesing di lapisan masyarakat
ini.
Sungguh pilu dan haru
sayang. Sejak jarak kita semakin jauh, dan tangan tak bisa menjangkau
disebabkan batasan pulau. Hatimu mulai garang, rindumu renggang, dan cintaku
semakin gersang. Mimpi kita, tidak lagi seperti sastra dan politik. Ya, pada keduanya
saling hidup dan menghidupkan, serta memainkan tokoh cerita. Namanya saja
berbeda, tapi isinya melekat pada keduanya. Ya, tetap saja berbeda bagimu. Sebab,
diseberang kau telah berubah haluan. Kau menyukai teh, bukan lagi kopi.
“Aku lebih suka teh, lebih
sehat dibanding kopi,” ucapmu tanpa bisa memberiku alasan yang lebih logis.
Menurutku, kopi juga banyak mengandung manfaat, seperti caffeine di dalam kopi sebagai senyawa psikoaktif, yang bersifat
stimulan mampu memberikan boost untuk
meningkatkan semangat kerja. Ya, ibarat semangatku ingin melihat senyummu lagi.
Ulfah, aku terlanjur telah kau
beri candu yang begitu pekat dan menikam. Doaku kini, ingin menghirup kopimu lagi,
sembari memegang gelas berukir zodiakmu. Bila tak sudi kumeneguk pelukmu,
biarlah pada kopimu saja. Aku tunggu di meja tamu, dengan bahan sastra dan
politik darimu. Sajikan juga rindu dalam kopimu. Aku terlalu candu, dan
biarkanlah aku membunuh rindu padamu. Atau cukuplah pada langit-langit rumah
berwarna biru mataku bertemu.***
Padang, 29/08/2016
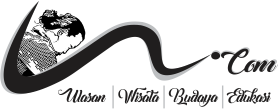






0 Comments
Jika bermanfaat tolong sebarkan dengan mencantumkan sumber yang jelas. Terima Kasih !